PS. Tulisan ini dibuat untuk memenuhi Diseminasi bertajuk Menjajaki Posdekonstruksi di UGM tahun 2023, yang kemudian tulisan ini dibukukan bersama tulisan lain dengan judul Sastra dalam Konstelasi Wacana (2024). Tampilan sampul, halaman kolofon, daftar isi, dan sedikit isi dari tulisan ini di dalam buku tersebut telah disertakan di bagian terakhir.
Abstrak
Penelitian ini mengupas buku puisi Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945-2045 karya Martin Suryajaya (2020) dengan teori hiperrealitas Baudrillard. Alasan dasar menggunakan objek material tersebut adalah buku tersebut melanggar hukum buku puisi sehingga buku tersebut tampak tidak sekadar buku puisi, namun bisa terlihat sebagai novel. Dengan menghimpun puisi dari penyair fiktif, Suryajaya sebenarnya mengkritisi antologi puisi dari sejarah sastra Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini lebih cocok menggunakan teori hiperrealitas Baudrillard dengan tujuan: melihat hiperrealitas (realistic, counterfeit, production, dan simulation) pada buku puisi Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945-2045 karya Martin Suryajaya (2020). Metode yang digunakan adalah metode diskursif, yakni untuk memahami karya sastra sebagai wacana sekaligus berusaha menemukan hubungan antara karya sastra dengan berbagai wacana yang ada sebelumnya dan sesudahnya. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa realistic, counterfeit, production, dan simulation akan membentuk hiperrealitas berupa menawarkan sejarah baru lewat penyusunan buku puisi dalam rentang yang panjang dalam seratus tahun.
Kata Kunci: buku puisi, Martin Suryajaya, posdekonstruksi, hiperrealitas
Abstract
This research examines the poetry book Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945-2045 by Martin Suryajaya (2020) with Baudrillard’s theory of hyperreality. The basic reason for using this material object is that the book violates the poetry book law so that the book does not appear to be just a poetry book, but can be seen as a novel. By collecting poetry from fictional poets, Suryajaya is actually criticizing poetry anthologies from Indonesian literary history. Therefore, this research is more suitable to use Baudrillard’s theory of hyperreality with the aim of: looking at hyperreality (realistic, counterfeit, production, and simulation) in the poetry book Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur 1945-2045 by Martin Suryajaya (2020). The method used is the discursive method, namely to understand literary works as discourses while at the same time trying to find the relationship between literary works and various discourses that existed before and after them. This research resulted in the finding that realistic, imitation, production, and simulation will form hyperreality in the form of offering a new history through the compilation of poetry books over a long span of one hundred years.
Keyword: poetry book, Martin Suryajaya, postdecontruction, hyperreality
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Buku puisi Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945-2045 (selanjutnya ditulis 3T: APOI) menentang hukum buku puisi – atau bisa disebut antologi puisi jika ditulis oleh sejumlah penyair. Menentang di sini adalah para penyair pada buku tersebut dimunculkan sebagai tokoh fiktif (hasil rekaan dari penyair riil) yang menulis puisi. Bukan hanya Suryajaya menempatkan diri seutuhnya sebagai penyair yang menulis puisi, melainkan juga berlindung di balik tokoh rekaannya. Jalan yang digunakan oleh Suryajaya tersebut adalah dekonstruktif sehingga bisa diteliti dengan cara dekonstruksi menggunakan hiperrealitas Baudrillard.
Karena di awal disebutkan menentang hukum buku puisi pada umumnya yang ditulis oleh sejumlah penyair, maka terlebih dahulu dijabarkan fenomena antologi puisi di Indonesia. Alih-alih menggunakan istilah ‘buku puisi’, peneliti menggunakan istilah ‘antologi puisi’ agar tidak tumpang-tindih antara yang ditulis seorang maupun sejumlah penyair.
Berdasarkan pengamatan peneliti melihat antologi puisi yang bertebaran, di luar buku puisi yang ditulis oleh seorang penyair, maka bisa ditarik ada tiga kecenderungan sebuah antologi puisi dihimpun: kesamaan latar belakang, 2) kesamaan tema, 3) sebagai penanda zaman, terutama sejarah sastra Indonesia.
Pertama, kesamaan latar belakang. Antologi semacam ini bertebaran sepanjang tahun, baik di sekolah, balai bahasa daerah, maupun yang dibukukan secara kolektif dengan biaya independen. Tujuannya biasanya sebatas agar puisi-puisi mereka bisa dibukukan, selain juga sebagai penanda bahwa mereka memiliki karya bersama. Kesamaan latar belakang seperti status (siswa, guru, pegawai, dlsb), asal daerah (Jawa, Maluku, Medan, dlsb), komunitas, jenis kelamin (perempuan, transgender, dlsb), dan lain-lain. Sebagai contoh, antologi puisi Peradaban Baru Corona: 99 Puisi Wartawan Penyair Indonesia (2020), Rahim Perempuan: Antologi Puisi Enam Perempuan Penyair Maluku (2019), kemudian ada Rindu untuk Ibu: Antologi Puisi Siswa (2012), dan masih banyak lagi dan cukup mudah dijumpai antologi serupa.
Kedua, kesamaan tema. Antologi semacam ini sering diprakarsai, salah satunya, oleh Sosiawan Leak, dengan mengangkat tema korupsi yang cukup variatif pada tiap antologinya. Tiga di antaranya: Puisi Menolak Korupsi 7: Negeri Tanpa Korupsi (2018); Puisi Menolak Korupsi 8 (2021); Korupsi di Korona: 94 Penyair Indonesia (2021). Dengan mengikat pada tema yang sama, yang sebagian besar berbicara tentang korupsi atau perlawanan penyair terhadap korupsi lewat puisi, berbagai latar belakang penyair yang berbeda bisa terhimpun. Dengan adanya antologi semacam itu, penyair yang tidak memiliki tempat di arena sastra nasional pun bisa turut berkontribusi asalkan mampu menulis sesuai tema yang telah ditentukan.
Ketiga, sebagai penanda zaman. Antologi semacam ini biasanya menghimpun puisi dari sejumlah penyair yang berpengaruh secara nasional pada sejarah sastra Indonesia. Sebut saja, Pujangga Baru (1963) yang dihimpun oleh H.B. Jassin. Majalah tersebut memuat: puisi (syair, pantun, dan sebagainya), prosa (cerita, roman, dan sebagainya), tonil, kupasan, dan timbangan kesusasteraan, serta pemandangan tentang seni umum dan sebagainya yang di dalamnya ada sejumlah penyair pada angkatan Pujangga Baru (1933-1942) (Jassin, 2013: 8). Alasan Jassin (2013: 7) menghimpun karya-karya tersebut adalah sebagai bentuk realisasi dari hasrat untuk menyatukan tenaga cerai-berai pengarang Indonesia sebelumnya yang telah kelihatan hasilnya dalam berbagai majalah, tidak hanya terbatas pada Majalah Pujangga Baru yang diprakarsai oleh Armijn Pane, Amir Hamzah, dan Sutan Takdir Alisjahbana pada Juli 1933.
Antologi lainnya ada Zamrud Khatulistiwa (1997) yang dikurasi dan dieditori oleh Sayuti, dkk. dengan memuat beberapa puisi dari sejumlah penyair. Sebut saja Sonny Farid Maulana, Imam Budi Santoso, Iswadi Pratama, dan penyair lainnya. Berbeda dengan buku Pujangga Baru yang dihimpun sendiri oleh H.B. Jassin dari berbagai majalah zaman saat itu, antologi ini sifatnya undangan terbuka, dipilih dari naskah puisi yang sudah dikirim oleh penyair. Sayuti, dkk (1997: x, xvi) menyebutkan bahwa antologi puisi Zamrud Khatuliswa merupakan hasil seleksi yang bernuansa koleksi, dengan tetap mempertimbangkan kaidah dan hukum komunikasi puitik untuk menyeleksikan ratusan judul puisi yang masuk.
Dari semua kecenderungan yang telah disebutkan di depan, para penyair adalah orang yang riil (nyata) sehingga mampu menulis puisi dengan gaya atau licentia poetica yang mereka usung. Itulah sebabnya, 3T: APOI muncul dengan perbedaan yang jelas kentara. Bahkan, untuk menegaskan bahwa semua penyair di dalam 3T: APOI adalah rekaan, Suryajaya memasukkan kata “obskur” yang menjadi bagian dari judul dan kemudian dijelaskan artinya sebagai berikut:
Obskur atidak jelas; samar-samar: ia adalah seorang penyair – karena kiprahnya tidak diketahui banyak orang.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Edisi XIII, 2045
Alih-alih kata “obskur” bisa ditemukan di KBBI, kata tersebut diserap oleh Suryajaya dari Bahasa Inggris[1] yang memiliki tiga arti:
- not known to many people
- not clear and difficult to understand or see
- to prevent something from being seen or heard
Sebenarnya, Suryajaya tengah memberi tawaran kepada Badan Bahasa untuk memasukkan kata “obskur” ke dalam KBBI lewat memberi pengertian tersendiri. Sebagai penegas, dengan memakai judul Terdepan, Terluar, Tertinggal, yang menyitir program pemerintah untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau, buku 3T: APOI juga menunjukkan bahwa puisi-puisi di dalamnya adalah puisi yang kemungkinan ada tapi jauh dari jangkauan, antara mungkin saja ada atau memang tidak ada. Dengan adanya penggunaan kata “obskur” dan 3T tersebut, semakin jelas bahwa ada anomali dan meta-puisi di dalam buku tersebut.
Anomali yang dimaksud di sini adalah garis samar, batas yang kabur antara satu dan lain. Bisa dikatakan, anomali terbentuk karena oposisi biner, dua hal yang semula bertentangan. Anomali ini, alih-alih bersifat hierarkis atau setara, menimbulkan batas antar keduanya semakin kabur. Ada keragu-raguan di dalamnya. Lihat saja, anomali yang terjadi: penyair riil – penyair rekaan, novel – puisi, dan sejarah perpuisian riil – sejarah perpuisian rekaan.
Suryajaya sebagai kreator atau penulis buku 3T: APOI bisa juga disebut sebagai penyair sebab dia menulis buku puisi. Masalahnya, puisi-puisi di dalamnya menggunakan nama penyair rekaan yang sebagian besar bertolak dari penyair riil. Dari penyair rekaan tersebut, alih-alih dikategorikan sebagai buku puisi, buku 3T: APOI sebenarnya layak untuk disebut sebagai novel nir-narasi, yang menghilangkan narasi antar penyair (untuk kasus novel menggunakan tokoh) yang saling menghubungkan sehingga menciptakan konflik. Karya sastra semacam ini belum ada sejauh pengamatan peneliti di Indonesia. Namun, jika melihat lebih jauh, karya serupa sudah ada di Multiple Choice (2016) karya Alejandro Zambra. Zambra memperlihat kerancuan memperlihatkan kerancuan atas pemisahan genre pada karya tersebut dengan memberi pilihan di sampul bukunya seperti berikut: a) fiksi, b) non-fiksi, c) puisi, d) semua yang ada di atas, e) bukan semua yang di atas. Jika kita membuka isi di dalamnya, pilihan antara fiksi, non-fiksi, dan puisi bisa masuk ke dalamnya, tanpa bisa dipisahkan. Buku tersebut berisi sejumlah pilihan ganda untuk pilihan kata, pilihan alur cerita, dan prosa. Zambra sebenarnya menyitir format tes TOEFL ITP untuk bahasa Inggris ke dalam bentuk buku yang tidak jelas genre apa yang hendak diusung.
Dikatakan sebagai buku puisi karena memuat sejumlah puisi, namun juga bisa dikatakan novel karena memuat 18 profil penyair rekaan serta memperiodisasikan mereka dalam rentang seratus tahun. Pembaca akan menghadapi puisi dan novel seakan-akan melebur menjadi satu dan batas antar keduanya menjadi kabur. Selain itu, periodisasi yang dihimpun akan membuat pembaca meninjau ulang, apakah periodisasi tersebut berpijak dari sejarah perpuisian Indonesia yang riil, mengingat sebagian besar penyair rekaan bertolak dari sana. Itulah sebabnya, buku 3T: APOI juga bisa dibilang sebagai karya yang mengkritisi sejarah perpuisian Indonesia yang mana redaktur bisa mengambil andil penuh terhadap penyair yang masuk ke dalamnya.
Kemudian, jika melihat gaya puitik yang digunakan Suryajaya dalam menulis puisi, ia sebenarnya tengah menempatkan posisi keseluruhan puisi tersebut dalam meta-puisi. Fakhreddine (2011: 205) mendefinisikan meta-puisi (puisi tentang puisi) sebagai keasyikan penyair dengan mediumnya dan seringkali menyuarakan kegelisahannya terhadap peran dan tempatnya dalam suatu tradisi sastra. Pandangan tersebut berpijak dari pernyataan Wellek (1971: 261) bahwa meta-puisi sebagian besar berkaitan dengan definisi diri penyair dan dengan tujuannya di jalan kepenyairan.
Pada konteks buku 3T: APOI, Suryajaya sebenarnya tengah menyuarakan kegelisahannya terhadap sejarah sastra Indonesia. Alih-alih menulis puisi dengan namanya sendiri seperti para penyair yang membukukan puisinya, Suryajaya menciptakan penyair fiktif untuk kemudian atas nama mereka puisi dituliskan. Lebih lanjut, profil yang menyertai seluruh penyair adalah bagian dari puisi yang dibangun. Dari sana, terlihat bagaimana kepekaan dan kepiawaian Suryajaya dalam mengolah data para penyair riil dan mempermainkannya menjadi buku puisi baru yang juga seolah-olah menciptakan sejarah sastra rekaannya sendiri.
Bisa dikatakan bahwa buku 3T: APOI tidak sekadar mendekonstruksi wajah perpuisian Indonesia dengan cara membongkar untuk kemudian membentuk wajah baru, namun juga turut menjauhinya sehingga seakan-akan buku tersebut bukan representasi wajah perpuisian Indonesia yang telah ada sebelumnya. Buku 3T: APOI berhasil meniti secara hati-hati jalan posdekonstruksi. Posdekonstruksi di sini bukan berarti melampaui dekonstruksi, melainkan potensi setelah berpijak dari dekonstruksi. Setelahnya, ada kekacauan yang disebabkan oleh anomali dari muasal oposisi biner sehingga penanda lebih menyenangkan karena bersifat parodi ketimbang menelisik petanda yang menyelubunginya. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan objek formal simulakra dari Baudrillard.
Tujuan
Dari latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk membongkar hiperrealitas (realistic, counterfeit, production, dan simulation) yang berkelindan di dalam buku puisi Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945-2045 karya Martin Suryajaya (2020) dengan menggunakan perspektif Baudrillard.
Landasan Teori
Penelitian ini menggunakan objek formal berupa hiperrealitas Baudrillard yang berpijak dari dekonstruksi Derrida. Sebelum menjangkau ke sana, terlebih dahulu ditelusuri bagaimana sebelum, saat, dan sesudah dekonstruksi supaya runtut konsep berpikir dalam penelitian ini.
1. Sebelum Dekonstruksi (Strukturalisme)
Saussure dikenal sebagai Bapak strukturalisme. Strukturalisme Saussurean adalah paham yang beranggapan bahwa kenyataan tertinggi dari realitas adalah struktur, sedangkan struktur adalah hubungan mutual dari konstituen, bagian-bagian, atau unsur-unsur pembentuk keseluruhan, sebagai penyusun sifat khas, atau karakter dan koeksistensi dalam keseluruhan bagian-bagian yang berbeda (Norris, 2017: 8–9). Saussure melihat bahwa ada kebermaknaan sebuah tanda bisa bersifat relasional dengan tanda lainnya, bukan karena kesamaan fisik antara tanda satu dengan yang lain dari makna atau konsepnya (Sukyadi, 2013: 3). Dalam artian, realitas dalam pandangan strukturalisme dibangun oleh hubungan hierarkis, yang mana satu unsur lebih luhur ketimbang unsur yang lain. Konsep ini dikenal sebagai oposisi biner, dua hal yang saling bertolak belakang atau memiliki hubungan hierarkis.
Berbicara strukturalisme Saussurean, tentu tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Saussure (1959: 51) mengatakan bahwa oposisi biner berisi unsur mekanis dan akustik yang saling mengkondisikan satu sama lain; variasi satu memiliki dampak yang diperlukan dan diperhitungkan pada yang lain. Sebagai contoh, Saussure menganggap bahwa tuturan tingkatannya lebih tinggi ketimbang tulisan. Hal ini dikarenakan tuturan, menurut Saussure, adalah kesatuan petanda dan penanda yang dianggap kelihatan menjadi satu dan sepadan, dan membangun sebuah tanda (Norris, 2017: 9). Oleh sebab itu, tuturan bagi Saussure lebih diutamakan karena dinilai lebih asali daripada tulisan yang dianggap sebagai representasi dari tuturan (Ungkang, 2013: 33).
Contoh lain dari oposisi biner adalah langue – parole, penanda – petanda, diakronis – sinkronis, sintagmatik – paradigmatik, dan sebagainya. Untuk contoh di luar linguistik, ada: baik – buruk, jiwa – badan, benar – salah, pria – wanita, dan lain sebagainya. Dengan melihat contoh-contoh tersebut, bisa dikatakan bahwa istilah yang pertama menjadi pusatnya, sedangkan istilah yang kedua hanya berperan sebagai penegas terhadap istilah pertama, pusatnya. Hal ini yang hendak dikritisi oleh Derrida.
2. Dekonstruksi (Posstrukturalisme)
Hadirnya dekonstruksi Derrida adalah untuk mengkritisi strukturalisme. Oposisi biner yang mana satu unsur lebih tinggi dari unsur lainnya membuat Derrida menyangkal konsep tersebut. Derrida melihat adanya bahwa istilah yang pertama, pada oposisi biner yang telah disebutkan di depan, adalah milik Logos – kebenaran, sedangkan istilah yang kedua adalah representasi palsu dari yang pertama atau bersifat inferior (Norris, 2017: 9). Oleh sebab itu, tradisi tersebut disebut logosentrisme yang menerangkan bahwa ada hak istimewa, sebagai pusat, dari istilah pertama dan pelecehan terhadap istilah kedua. Prinsip tersebut akan membuat orang berpikir dikotomis, segalanya harus jelas posisinya sebagai hitam dan putih, yang kemudian menjatuhkan kepada konsep berpikir bahwa segala sesuatunya haruslah memiliki hierarki, yang berakhir pada dominasi dari suatu posisi terhadap posisi yang lain (Wididharma, 2005: 40).
Derrida mempertanyakan logosentrisme yang bermuasal dari filsafat Barat tersebut untuk bisa ditafsirkan ulang lewat pembacaan ulang. Penafsiran ini pun bergantung kepada setiap orang dalam pembacaannya. Secara umum, Derrida mengklaim bahwa tidak ada hal lain kecuali teks karena teks adalah satu-satunya realitas (Bradley, 2008: 112). Tidak ada yang di luar teks. Dengan kata lain, Derrida, lewat dekonstruksinya, menolak oposisi biner karena baginya kedua unsur tersebut adalah setara, tidak ada satu unsur yang lebih tinggi dari unsur yang lain pada suatu struktur. Hal ini dikarenakan keduanya sama pentingnya dengan mengembalikan lagi kepada pembaca. Semisal, antara pria – wanita, tidak ada yang lebih luhur karena keduanya menempati posisi setara, memegang perannya masing-masing. Peran di sini tidak semata-mata pria melakukan tugasnya sebagai pria terus-menerus, maupun sebaliknya, namun juga pria juga bisa melakukan peran wanita, contohnya memasak.
Lebih lanjut, jika tuturan bagi Saussure adalah yang asali, maka bagi Derrida, tulisan adalah prakondisi dari bahasa, dan bahkan telah ada sebelum tuturan (Norris, 2017: 10). Tulisan bermula dari permainan bebas dari unsur-unsur bahasa dan komunikasi yang kemudian mengalami proses perubahan makna terus-menerus dan perubahan ini menempatkan diri di luar jangkauan kebenaran mutlak (logos).
Yang menjadi pertanyaan, mengapa suatu tulisan atau teks dianggap hal yang asali? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Hoed (2007: 27) yakni sebagai berikut: tulisan adalah bahasa yang secara maksimal memenuhi dirinya sendiri karena tulisan menguasai ruang secara maksimal pula; tidak hanya terdapat di dalam pikiran manusia, tetapi juga dikonkretkan di atas halaman; tulisan memenuhi dirinya sendiri karena tulisan terlepas dari penulisnya begitu ia berada di ruang halaman, namun ketika dibaca, tulisan langsung terbuka untuk dipahami oleh pembacanya.
Dengan konsep tulisan adalah yang asali yang diusung oleh Derrida tersebut, bisa dikatakan bahwa pemaknaan terhadap sesuatu dikembalikan kepada pembaca. Dari sini, muncul keterbukaan, celah, atas dekonstruksi itu sendiri. Dekonstruksi menolak pemaknaan tunggal seperti yang telah terjadi pada logosentris, namun dekonstruksi juga membebaskan apa yang hendak terjadi setelah terbuka pemaknaan. Singkatnya, dekonstruksi erat hubungannya dengan pembacaan karena melibatkan pembaca. Lebih lanjut, Sumarwan (2007: 18) melihat ada double reading di dalam proses dekonstruksi: satu sisi bermaksud menampilkan kembali atas tafsiran dominan atas suatu teks, namun di sisi lain, meninggalkan tatanan, memperlihatkan titik lemah, dan kontradiksi dalam tafsiran dominan tersebut, lalu menyajikan pembacaan yang lain. Dengan kata lain, dekonstruksi bukanlah destruktif terhadap struktur yang ada, namun lebih kepada pengacakan terhadap struktur tersebut sekaligus melakukan penataan ulang.
Permasalahannya, sejauh mana pembacaan kedua tersebut hinggap? Hal tersebut akan dibahas pada bagian posdekonstruksi di bawah ini.
3. Posdekonstruksi (Penyederhanaan dan Potensi Setelah Dekonstruksi)
Derrida menawarkan dekonstruksi sebagai bentuk penyangkalan terhadap pemaknaan tunggal, logosentris, atau yang terpusat sehingga unsur yang mengikutinya menjadi tertindas, tersisih, maupun terabaikan. Oleh sebab itu, dekonstruksi melakukan double reading, untuk mengoreksi ulang tentang struktur yang terjadi. Permasalahan timbul dari sini, yakni sejauh mana dan proses dekonstruksi berhenti di mana, itu yang jadi soal. Dengan melepaskan pemaknaan kepada pembaca, dekonstruksi bisa terjadi terus-menerus, tanpa bisa berhenti.
Derrida sendiri sulit mendefinisikan atau menerjemahkan dekonstruksi secara konkret. Wididharma (2005: 41) menjelaskan secara gamblang lewat dua poin berikut:
Pertama, karena istilah apapun yang digunakan untuk menerjemahkan atau mendefinisikannya, dengan menawarkan suatu makna ataupun konsep yang bersifat definitif, dengan sendirinya membuka peluang untuk berlangsungnya suatu operasi dekonstruktif.
Kedua, Derrida sendiri menolak adanya konsep yang terlepas atau melampaui kata-kata. Ia menolak adanya suatu konsep dekonstruksi yang hadir ke dunia yang berada di luar kata-kata yang terangkum di dalam berbagai frasa ataupun kalimat.
Dengan kata lain, Derrida tidak ingin istilah dekonstruksi yang telah terdefinisikan olehnya bisa didekonstruksi ulang karena dijelaskan oleh kata-kata. Bisa dibilang, inilah sisi kontradiktif dari dekonstruksi. Di satu sisi, menawarkan, namun di sisi lain, menyangkal. Oleh sebab itu, proses dekonstruksi terbilang rumit dan tidak memiliki ujung, bisa menuju ke segala arah. Punday (2003: 21) menyebut bahwa dekonstruksi adalah jalan buntu.
Dengan berpijak dari dekonstruksi, muncul posdekonstruksi. Posdekonstruksi adalah jalan ringkas setelah begitu rumit memahami dekonstruksi. Punday (2003: 26) mengatakan bahwa kritik atas dekonstruksi, yakni posdekonstruksi, harus memiliki relevansi dengan dunia, yakni dengan cara menyederhanakan ruang dekonstruktif menjadi bidang sederhana yang bermakna secara analogis. Dengan kata lain, dekonstruksi yang bertumpu pada teks, dengan asumsi dasar bahwa tiada hal lain di luar teks karena realitas terselubungi oleh teks, harus dihubungkan kepada realitas yang sesungguhnya, kepada dunia. Hal inilah yang nantinya membuat dekonstruksi lebih sederhana dan mudah dipahami karena menghubungkan kepada hal-hal dunia sesuai dengan teksnya.
Jika dijabarkan secara runut, jalan yang akhirnya bermuara kepada posdekonstruksi adalah sebagai berikut:
Pertama, logosentrisme dengan asumsi bahwa ada pemaknaan tunggal sehingga timbul oposisi biner, dikotomi terhadap struktur yang tersusun, sehingga ada satu unsur yang lebih tinggi dan unsur yang lain lebih rendah karena bersifat memperkuat unsur yang pertama.
Kedua, dekonstruksi hadir untuk menyangkal sekaligus menawarkan opsi bahwa logosentrisme tidak terjadi karena dua unsur sebenarnya sama pentingnya, setara, dan tidak ada yang lebih tinggi dari unsur yang lain.
Ketiga, posdekonstruksi hadir untuk menyederhanakan ujung dari dekonstruksi dengan cara mengembalikan teks kepada dunia.
Dengan demikian, posdekonstruksi adalah jalan untuk mengaitkan teks yang berkelindan dengan konteks yang terjadi pada dunia. Pertanyaannya, apa potensi setelah adanya posdekonstruksi?
Banyak teori yang bertumpu dari dekonstruksi untuk mengaitkan kepada konteksnya. Beberapa contohnya ada pada rumpun poskolonialisme, dan feminisme, posmodernisme. Pada poskolonialisme, bisa dilihat bagaimana pengaruh dekonstruksi kepadanya, yakni mendekonstruksi oposisi Barat – Timur, penjajah – terjajah, baik – buruk, beradab – biadab, rajin – malas, dan semacamnya. Said mengibaratkan dekonstruksi sebagai sebuah operasi militer dekolonisasi, yakni: di satu sisi, serangan diarahkan untuk menghancurkan dan mengusir kaum kolonis yang telah menguasai tanah jajahan dan penduduknya, tapi di sisi lain, serangan ini juga dimaksudkan untuk membebaskan para tawanan dan merebut kembali tanah itu secara paksa (Sumarwan, 2007: 18).
Selanjutnya, feminisme mempermasalahkan adanya ketimpangan antara hubungan laki-laki dan perempuan. Sumarwan (2007: 20) mengatakan bahwa feminisme memperlihatkan kekerasan oposisi tersebut dan berusaha mengatasi ketimpangannya. Tidak hanya menunjukkan ketimpangan tatanan, namun juga membongkarnya agar keduanya bisa setara.
Terakhir, posmodernisme. Istilah posmodernisme tersebut diperkenalkan oleh Lyotard yang menunjuk pada keadaan budaya kita setelah mengalami perubahan, sejak akhir abad kesembilan belas, yang mengubah cara pandang pada ilmu sains, sastra, dan seni (Lyotard, 1984: xxiv). Selain itu, pengertian lain dari posmodernisme adalah paham yang menggambarkan seluruh gerakan ilmu pengetahuan yang menentang modernisme dan ditandai dengan adanya bentuk-bentuk yang kompleks pada kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni (Hidayat, 2019: 45–46). Ciri posmodernisme yang lain adalah relativisme, terutama pada hal realitas budaya (nilai-nilai, kepercayaan, dan lainnya) (Setiawan & Sudrajat, 2018: 33).
Oleh sebab itu, posmodernisme mengangggap bahwa semua hal bisa mengalami perubahan, tidak selalu menemui titik yang mutlak, karena bergantung dari keterkaitan dengan hal lainnya. Modernisme yang cenderung kaku, dogmatis, dan berpusat pada satu hal, hendak dikritisi atau dilawan oleh posmodernisme.
4. Hiperrealitas Baudrillard
Salah satu teoretikus posmodernisme adalah Baudrillard. Baudrillard menyatakan bahwa dalam masyarakat postmodern, nilai tanda (sign-value) dan nilai-simbol (symbolic-value) telah menggantikan nilai-guna (use-value) dan nilai-tukar (exchange-value) (Hidayat, 2019: 57). Baudrillard memandang bahwa masyarakat hidup dalam simulasi yang dicirikan dengan ketidakbermaknaan atau hilangnya identitas dan jati diri manusia pada masa kontemporer ini (Setiawan & Sudrajat, 2018: 32).
Pemikirannya tersebut dikenal dengan hiperealitas. Hiperrealitas ini ditentukan dari empat citra dari penampilan, sebagai berikut: 1) realistic yaitu keadaan sebenarnya, 2) counterfeit yaitu tahap alami yang dapat ditemukan lewat imitasi, 3) production yaitu tahap produksi, dan 4) simulation yang merupakan simulacra dari simulasi, pembuatan informasi dan kode (Fitria, 2015: 89). Dari citra satu sampai tiga adalah citra yang sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sedangkan citra keempat adalah simulasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Bisa dikatakan bahwa pemikiran Baudrillard adalah nilai simbol (baju, ponsel, dan hal kebendaan lainnya) yang dikenakan bisa membentuk keadaan manusia yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itulah sebabnya, Baudrillard mendefinisikan sebagai hiperrealitas. Baudrillard (1994: 22) menjelaskan bahwa hiperrealitas dan simulasi adalah pencegah dari setiap prinsip dan tujuan, dengan melawan kekuatan yang mereka gunakan sangat baik dalam waktu yang lama. Oleh sebab itu, hiperrealitas bisa terjadi dan tercipta dalam waktu yang lama yang kemudian juga bisa digunakan untuk buku puisi 3T: APOI yang menyangkut sejarah perpuisian Indonesia.
Konsep hiperrealitas (Saragih, 2018: 22) tidak bisa dipisahkan dari konsep lain yang membentuknya, yakni konsep simulasi, sedangkan simulasi sendiri adalah penciptaan model-model kenyataan yang tanpa asal-usul atau referensi realitas – hiperrealitas. Lebih lanjut, Saragih menjelaskan bahwa tanda-tanda realitas dalam konteks simulasi bukanlah tanda-tanda yang melukiskan sebuah realitas di luar dirinya, tetapi tanda yang mengacu pada dirinya sendiri atau salinan dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, simulasi adalah strategi untuk menuju hiperrealitas.
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan buku puisi Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945-2045 karya Martin Suryajaya (2020) sebagai objek material disertai hiperrealitas dari perspektif Baudrillard. Data primer diambil dari kutipan berupa potongan puisi maupun profil penyair di dalamnya yang berada di buku puisi tersebut dengan didukung oleh data sekunder meliputi berbagai referensi buku puisi yang berhubungan dengan sejarah perpuisian Indonesia.
Untuk dapat melihat hiperrealitas pada buku 3T: APOI tidak bisa hanya secara holistik, namun secara parsial, yakni pada beberapa puisi dan profil penyair rekaan yang cenderung mengalaminya. Selain itu, tidak semua puisi diperlakukan sama oleh Suryajaya, dalam artian, ada yang berpijak dari realitas masa lalu, ada yang rekaan belaka, sehingga beberapa di antaranya sulit ditelusuri pijakan muasalnya.
Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode diskursif. Faruk (2012: 68) menjelaskan bahwa metode ini berkutat pada memahami karya sastra sebagai wacana sekaligus berusaha menemukan hubungan antara karya sastra dengan berbagai wacana yang ada sebelumnya dan bahkan sesudahnya.
Tinjauan Pustaka
Peneliti memisahkan tinjauan pustaka berdasarkan objek material dan objek formal yang digunakan. Buku 3T: APOI sebagai objek material pernah diteliti sebelumnya. Satu-satunya penelitian yang ditemukan adalah penelitian Prasetyo (2021) yang berjudul Wacana Kanonisasi Sastra Indonesia dalam Buku Terdepan, Terluar, Tertinggal (2020) karya Martin Suryajaya: Pembacaan Puitika Posmodern. Penelitian tersebut menggunakan konsepsi puitika posmodern Linda Hutcheon yang menghasilkan temuan bahwa buku 3T: APOI diciptakan dalam bentuk historiographic metafiction, menggunakan sekaligus menyimpangkan sejarah sastra Indonesia yang dihadirkan dengan bentuk metafiksi. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan hiperrealitas Baudrillard untuk melihat realitas asali, realitas semu, dan realitas yang benar-benar menjauhi dari titik semula.
Objek formal hiperrealitas Baudrillard, terutama dalam kajian sastra, tidak banyak ditemukan. Hal ini dikarenakan teori tersebut lebih banyak digunakan di luar kajian sastra, terutama film, media, culture studies, dan semacamnya. Oleh sebab itu, dengan meninjau hiperrealitas Baudrillard pada kajian sastra, hanya ditemukan satu penelitian, yakni penelitian Suharmono (2015) yang berjudul Masyarakat Konsumen dalam Novel Jalan Menikung Karya Umar Kayam (Tinjauan Postmodern Jean Baudrillard). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Jalan Menikung mengalami perubahan nilai yang terjadi dalam bentuk konsumerisme. Konsumerisme tersebut berupa kegiatan mengonsumsi pakaian, makanan, minuman, bangunan tertentu, barang mewah tertentu, pesta pora, pemanfaatan kekuasaan, dan pergaulan kelas atas.
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Realistic
Realitas dasar yang digunakan pada buku puisi 3T: APOI adalah penyair kanon dan kritikus sastra Indonesia. Penyair kanon di sini adalah penyair yang puisi-puisinya sudah dikenal luas oleh masyarakat luas. Beberapa di antaranya yang kentara terlihat: kritikus sastra bisa mengarah kepada HB Jassin, kemudian untuk penyair ada Sutardji Colzoum Bachri, Afrizal Malna, dan Dorothea Herliany Rosa. Selain itu, ada Ida Nasution, penyair perempuan yang pernah menjadi kekasih Chairil Anwar.
Di luar itu, realitas dasar yang berpijak dari penyair telah melebur menjadi hiperrealitas sehingga sulit untuk ditelusuri. Realitas dasar juga bisa dilihat dari tahun disusun, 1945, yang bertolak dari tahun kemerdekaan Indonesia.
Lihat puisi Pagi berikut yang ditulis oleh Ida Nasution.
Ada satu pedalaman yang tak sampai diucapkan,
tempat gerimis menitik jatuh
dan sepi juga tinggal tepi
1945
2. Counterfeit
Realitas dasar tersebut mengalami penyimpangan sehingga menutupi realitas yang sebenarnya, menjadi samar-samar. Bisa disebut samar-samar karena hampir keseluruhan penyair adalah tiruan dari penyair riil. Hal ini bisa dilihat dari profil dan gaya puitik yang diusung oleh penyair tersebut. Ada yang diubah namanya sedemikian rupa sehingga sulit diketahui meniru siapa.
Ida Nasution adalah pengecualian. Di dalam buku 3T: APOI, Ida dicirikan benar-benar mirip dengan sosok riilnya, yang sama-sama bernama Ida Nasution. Hal tersebut bisa dilihat (Suryajaya, 2020: 19) pada kesamaannya bahwa Ida lahir di Sumatra Utara tahun 1924, kuliah di Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte[2], Universiteit van Indonesie[3], meninggal dalam suatu perjalanan malam dari Jakarta ke Bogor, dan dikenal sebagai kekasih Chairil Anwar. Permasalahannya kemudian, apakah puisi Ida Nasution di buku 3T: APOI adalah puisi Ida Nasution yang asli atau tidak. Kepastian terkait keaslian puisi tersebut sulit ditelusuri karena di internet tidak ditemukan data tersebut. Kecuali, Suryajaya menemukan arsip puisi Ida Nasution di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin atau tempat arsip lain.
Untuk penyair lainnya, ada Ircisor Gulagat yang besar kemungkinan meniru sosok Sutardji Colzoum Bachri. Disebut besar kemungkinan karena kesamaan Ircisor dengan Sutardji hanya terdapat pada dua hal (Suryajaya, 2020: 47–48) yakni: pertama, pada belakang belakang buku Ircisor Gulagat[4] terdapat potret[5] dirinya sendiri, 2) ditulis dalam bahasa yang tidak kita kenali sehingga terdengar sepintas lalu seperti mantra[6]. Perbedaan yang mencolok adalah puisi-puisi Ircisor sama sekali tidak bermakna, bahkan sulit terbaca sebagai kesatuan bahasa. Hal ini bisa dilihat (Suryajaya, 2020: 50) pada pusi Samkara Bikara berikut: Dubolu owolai murusu/ Mimalah ursina sijulai-julai/ Kutindu naafi hiluahmana/ Usi-usi toonpari yato-yato//. Dengan kata lain, Suryajaya menarik gaya puitik Ircisor dari gaya puitik Sutardji ke titik ekstrim, yakni tidak bermakna dari kerancuan bahasa yang digunakan.
Kemudian, ada Yusrizal yang meniru sosok Afrizal Malna. Hal ini bisa dilihat (Suryajaya, 2020: 83) kesamaan kedua sosok sebagai berikut: sama-sama lahir pada tahun 1957, kemudian Yusrizal dengan rentetan karya seperti Yang Berdiam dalam Mikroba (1990)[7], Kalung dari Terjemahan (1998)[8], Museum Penghancur Lubang dari Separuh Bantal Berasap (2013)[9], Pagi yang Miring ke Berlin (2017)[10], dan Nyanyi Sunyi (2024)[11].
Lalu, ada Rina Novita Herliany yang merupakan tiruan dari Dorothea Rosa Herliany. Hal ini bisa dilihat (Suryajaya, 2020: 129) kesamaan kedua sosok sebagai berikut: sama-sama lahir di Magelang, kemudian Rina banyak melakukan diplomasi budaya dengan pusat-pusat kebudayaan asing di Indonesia, mendaftar program residensi di berbagai negeri, mengupayakan penerjemahan atas karya-karyanya ke dalam berbagai bahasa, yang mana juga dilakukan oleh Dorothea. Selain itu, puisi-puisi Rina yang termuat di dalam buku 3T: APOI, adalah plesetan dari karya-karya Dorothea. Lihat saja pada puisi Niqab Ilalang (Suryajaya, 2020: 132–133) yang merupakan plesetan dari Nikah Ilalang (1995), dan Sebuah Radio, Belum Kumatikan (Suryajaya, 2020: 134) yang merupakan plesetan dari Kill the Radio, (Sebuah Radio, Kumatikan) edisi dwibahasa (2001).
3. Production
Di tahap ini, ada proses produksi sehingga mengabaikan realitas dasar atau sulit untuk ditelusuri lagi. Pada buku 3T: APOI, ada sosok penyair yang cenderung karikaturis dengan nama: Nutrisari (Suryajaya, 2020: 54–63).
Berikut petikan puisinya yang berjudul Kami Tidak Mengandung Sianida
Sebuah pengumuman bagi segenap makhluk
Kami tidak mengandung sianida
Tidak juga babi
ataupun psikotropika
…
Ini suatu pengumuman saja.
Siapa tahu berguna
Barangkali memang bermartabat
Maaf baru bisa begini
1980
Selain itu, juga sekolompok penyair yang oleh Suryajaya (2020: 137) dinamakan Yayasan Pancaroba, perkumpulan penyair dan pegiat sastra yang alih-alih menghasilkan puisi, malah konsisten memproduksi proposal, berupa permohonan dukungan pendanaan, pembiayaan residensi, dan sejenisnya.
4. Simulation
Di tahap ini sudah tidak memiliki hubungan dari realitas dasar. Dia melepaskan realitas dasar sehingga tampak seperti realitas baru. Dengan adanya pembuatan profil penyair disertai puisinya, seakan-akan mereka adalah nyata dan Suryajaya sebagai pengarsip. Di tahap ini, pembaca akan kebingungan, apakah Suryajaya sebagai penulis atau pengarsip puisi, meski arsip puisi terlampau jauh tahun ke depan (2045).
Dengan demikian, hiperrealitas yang terjadi adalah buku 3T: APOI tampak seperti novel, alih-alih buku puisi. Selain itu, tampak juga bahwa Suryajaya tidak hanya sebagai menulis puisi untuk penyair fiktif, namun juga mengarang sejarah perpuisian Indonesia. Hal ini terlihat dari rentang tahun yang panjang selama seratus tahun, 1945-2045.
KESIMPULAN
Dari hasil temuan tersebut, bisa dikatakan bahwa penulisan buku 3T: APOI menggunakan teknik dekonstruksi, yakni mengkritisi sejarah perpuisian Indonesia. Proses ini dengan menyangkal sejarah tersebut lewat penyair fiktif, ada yang bermuasal dari realitas dasar dan ada yang terlepas dari realitas, dengan menawarkan sejarah baru lewat penyusunan puisi dalam rentang yang panjang dalam seratus tahun.
Selain itu, Suryajaya juga terlihat menciptakan hiperrealitas dengan cara berpijak dari realitas dasar tersebut untuk kemudian membentuk realitas yang benar-benar baru, terlepas dari muasalnya.
DAFTAR PUSTAKA
Baudrillard, J. (1994). Simulacra and Simulation. (S. F. Glaser, Ed.) (english tr). Michigan: The University of Michigan.
Bradley, A. (2008). Derrida’s of Grammatology. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Fakhreddine, H. J. (2011). Defining Metapoesis in the ’Abbāsid Age. Journal of Arabic Literature, 42(2–3), 205–235.
Fitria, H. (2015). Hiperrealitas dalam Social Media (Studi Kasus: Makan Cantik Di Senopati Pada Masyarakat Perkotaan). Informasi: Kajian Ilmu Komunikasi, 45(2), 87–100.
Hidayat, M. A. (2019). Menimbang Teori-Teori Sosial Postmodern: Sejarah, Pemikiran, Kritik Dan Masa Depan Postmodernisme. Journal of Urban Sociology, 2(1), 42.
Hoed, B. H. (2007). Tinjauan dari Kacamata Linguistik: Derrida vs Strukturalisme Saussure. Basis, 16–33.
Jassin, H. B. (2013). Pujangga Baru. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya.
Lyotard, J.-F. (1984). The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Norris, C. (2017). Membongkar Teori Dekonstruksi Jacques Derrida. (I. Muhsin, Ed.), Ar-Ruzz Media Group (Vol. 4). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media Group.
Prasetyo, M. A. (2021). Wacana Kanonisasi Sastra Indonesia dalam Buku Terdepan Terluar Tertinggal (2020) karya Martin Suryajaya: Pembacaan Puitika Posmodern. Universitas Gadjah Mada.
Punday, D. (2003). Narrative After Deconstruction. Albany: State University of New York Press.
Saragih, M. W. (2018). Hiperrealitas dan Kuasa Kapitalisme dalam Film in Time (2011). Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya, 8(Juni), 17–29.
Saussure, F. De. (1959). Course in General Linguistics. (W. Baskin, Ed.). New York: Philosophical Library.
Sayuti, S. A., Simatupang, L., Rahmanto, B., Suwondo, T., & Mardianto, H. (Ed.). (1997). Zamrud Khatulistiwa. Yogyakarta: Taman Budaya, Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.
Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Ilmu Pengetahuan. Jurnal Filsafat, 28(1), 25–46.
Suharmono. (2015). Masyarakat Konsumen dalam Novel Jalan Menikung Karya Umar Kayam (Tinjauan Postmodern Jean Baudrillard). Universitas Gadjah Mada.
Sukyadi, D. (2013). Dampak Pemikiran Saussure bagi Perkembangan Linguistik dan Disiplin Ilmu Lainnya. Parole, 3(2), 1–19.
Sumarwan, A. (2007). Membongkar yang Lama, Menenun yang Baru. Basis, 16–25.
Suryajaya, M. (2020). Terdepan, Terluar, Tertinggal: Antologi Puisi Obskur Indonesia 1945-2045. Jakarta: Anagram.
Ungkang, M. (2013). Dekonstruksi Jaques Derrida sebagai Strategi Pembacaan Teks Sastra. Jurnal Pendidikan Humaniora, 1(1), 30–37.
Wellek, R. (1971). Discriminations: Futher Concepts of Criticism. New Halen: Yale University Press.
Wididharma, N. (2005). Dua Gerbang Dekonstruksi: Derrida Nagarjuna. Basis, 38–45.
[1]https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obscure
[2] Fakultas Sastra dan Filsafat.
[3] Universitas Indonesia.
[4] Buku tersebut berjudul sama dengan nama penyairnya.
[5] Sama halnya dengan buku puisi O Amuk Kapak (buku tersebut sebenarnya menggabungkan tiga buku Sutardji, yakni: O (1966-1973), Amuk (1973-1976), dan Kapak (1976-1979)) yang terbit tahun 1981. Di buku tersebut, terpajang potret Sutardji di sampul depan.
[6] Hal ini mirip dengan kredo puisi Sutardji yakni mengembalikan asal mula kata sebagai mantra.
[7] Plesetan dari Yang Berdiam dalam Mikropon (1990).
[8] Plesetan dari Kalung dari Teman (1998).
[9] Plesetan dari gabungan karya Lubang dari Separuh Langit (2005), Pada Bantal Berasap (2009), Museum Penghancur Dokumen (2013).
[10] Plesetan dari Pagi yang Miring ke Kanan (2017)
[11] Berbeda dengan yang lain, Nyanyi Sunyi adalah judul buku puisi karya Amir Hamzah (1937) dan tidak didapatkan plesetannya pada karya Afrizal Malna. Meski begitu, bukan berarti Suryajaya semena-mena atau tanpa pertimbangan memasukkan Nyanyi Sunyi ke dalam puisi Yusrizal. Pertimbangan yang dilakukan Suryajaya adalah Afrizal Malna dengan gaya puisi gelapnya besar kemungkinan berpijak dari Nyanyi Sunyi Amir Hamzah. Oleh sebab itu, Suryajaya memasukkan Nyanyi Sunyi ke dalam puisi Yusrizal.
sampul buku
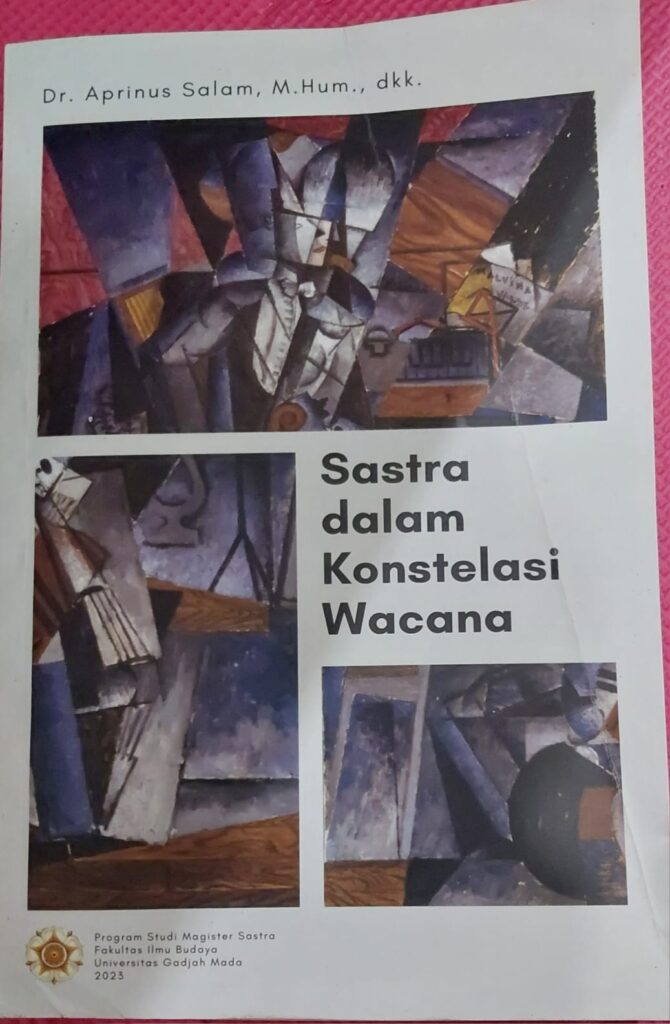
halaman kolofon
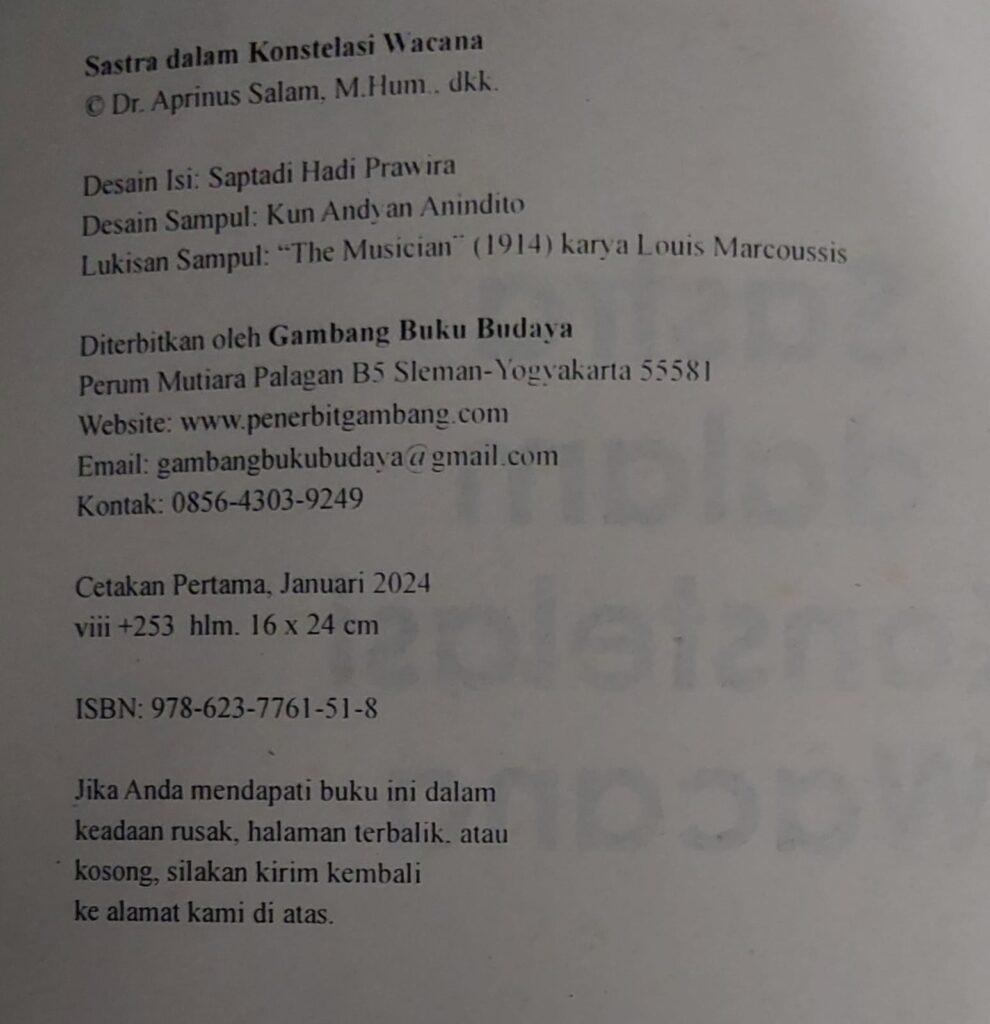
daftar isi (1)
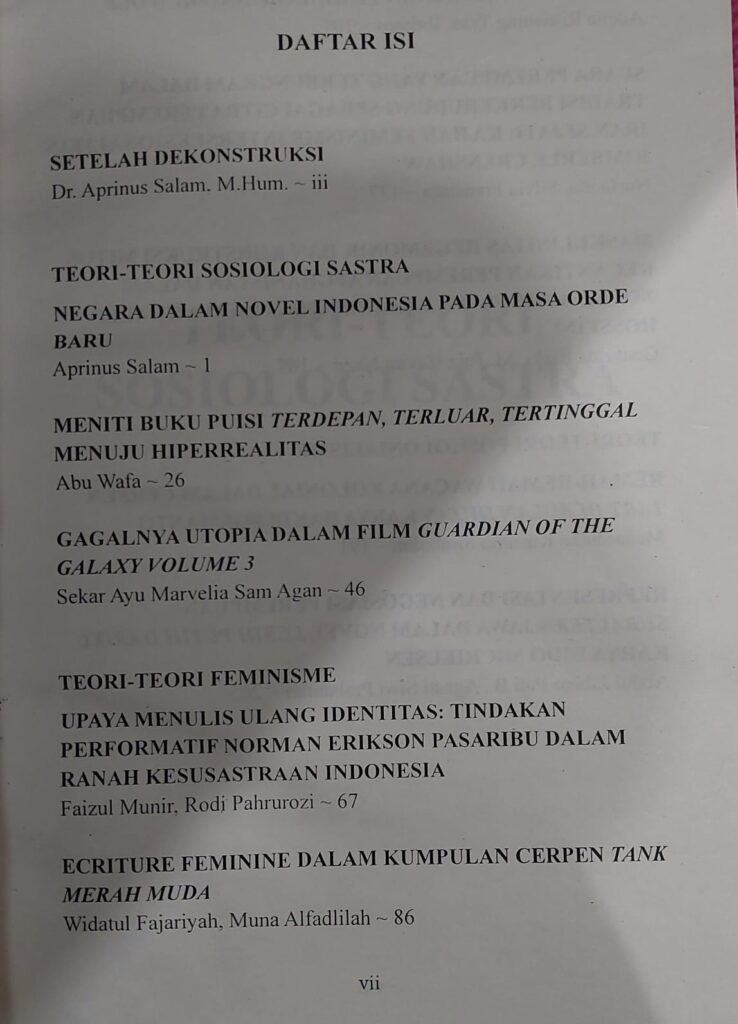
daftar isi (2)
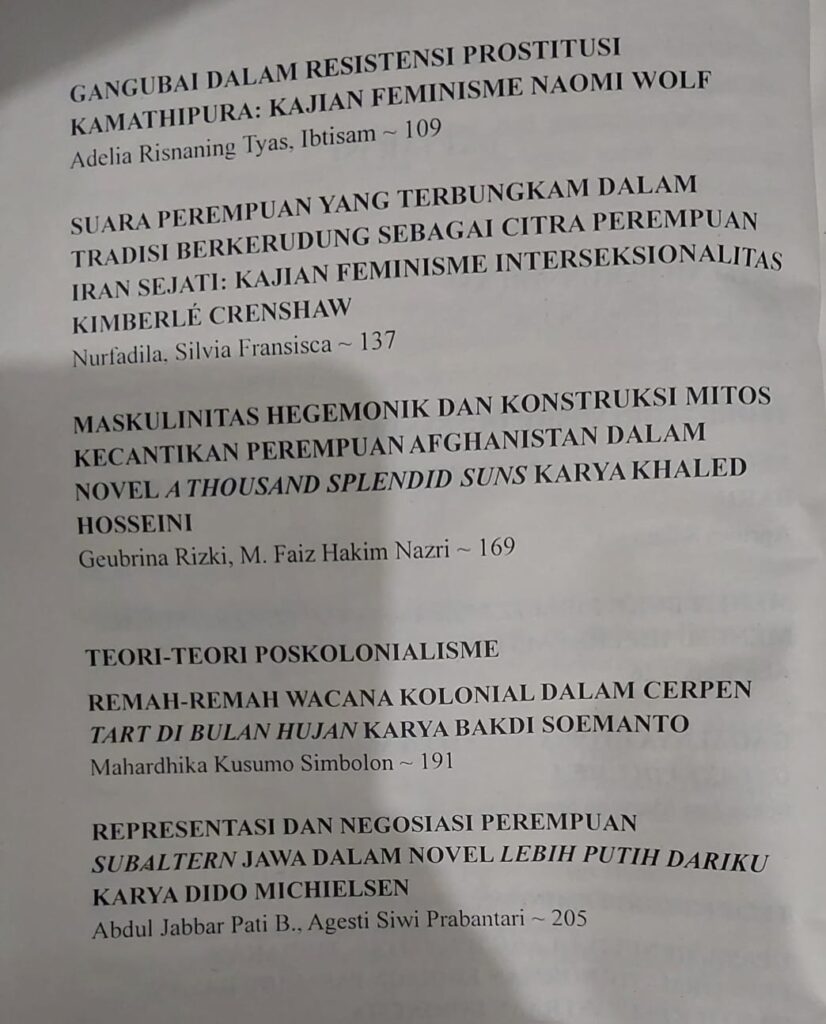
halaman depan tulisan
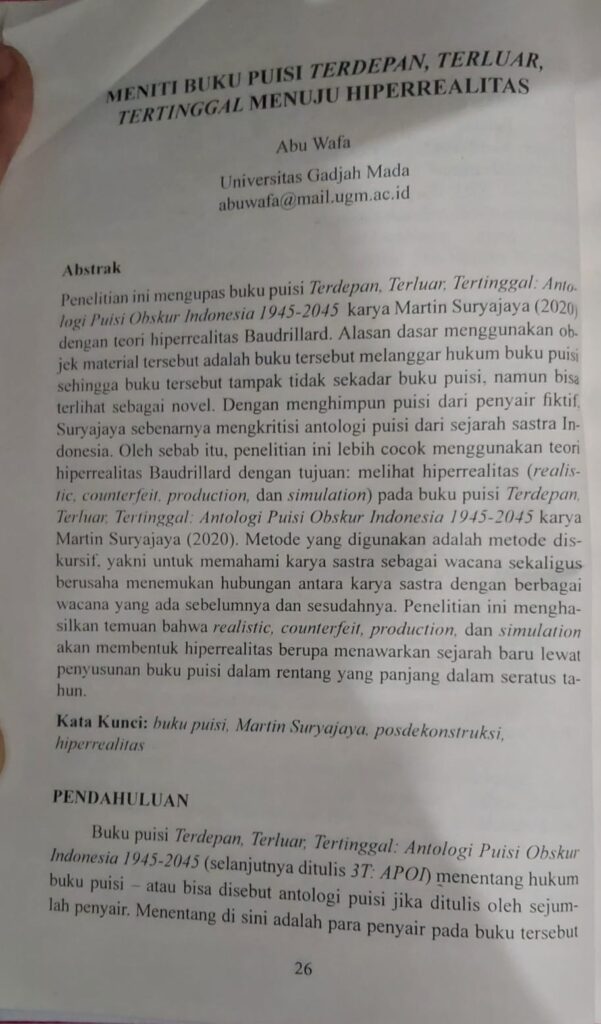
halaman belakang dan daftar pustaka
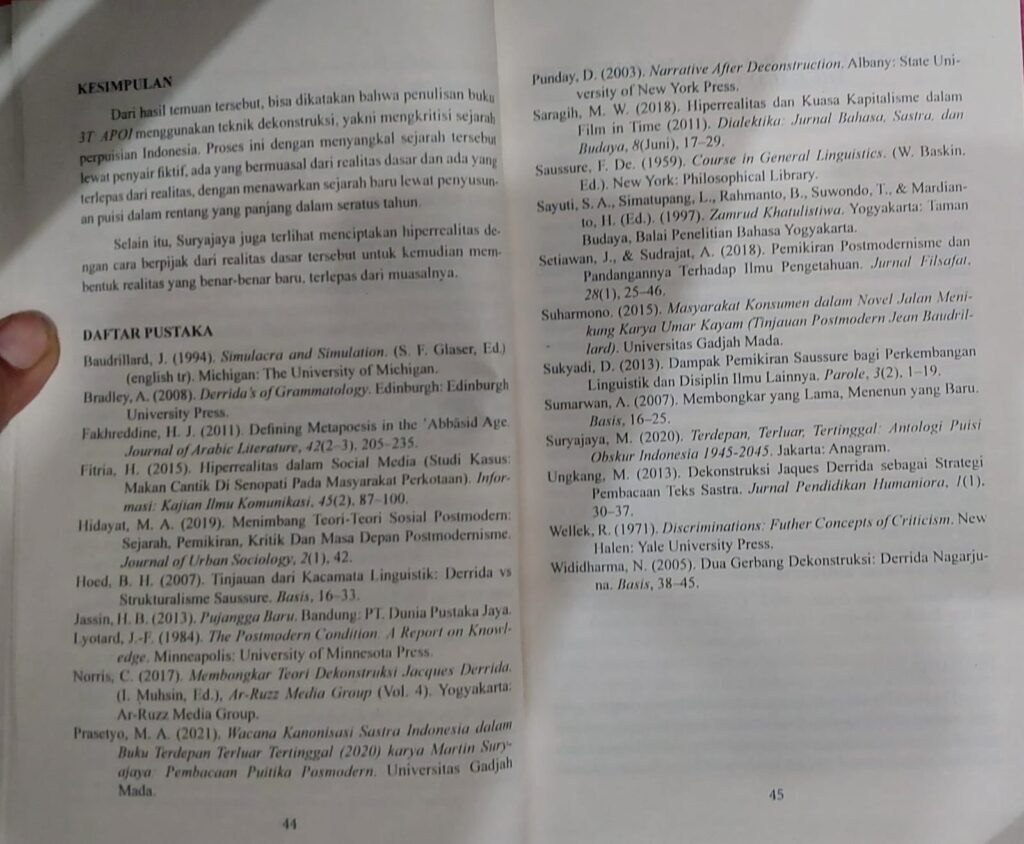
Tinggalkan Balasan